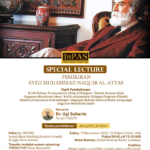Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi
 Inpasonline.com-Seorang dosen filsafat Islam di sebuah universitas Islam tiba-tiba memulai kuliahnya dengan kata-kata yang provokatif. Ia mengatakan:”Kita sekarang berlajar filsafat, maka masukkan iman kalian ke dalam saku terlebih dahulu.” Tidak jelas apa yang dimaksud, ia pun meneruskan kuliahnya.
Inpasonline.com-Seorang dosen filsafat Islam di sebuah universitas Islam tiba-tiba memulai kuliahnya dengan kata-kata yang provokatif. Ia mengatakan:”Kita sekarang berlajar filsafat, maka masukkan iman kalian ke dalam saku terlebih dahulu.” Tidak jelas apa yang dimaksud, ia pun meneruskan kuliahnya.
Apa yang dikuliahkan itu tidak penting. Tapi cara berfikir dosen itu penting dibahas. Apa yang perlu dicatat pertama-tama adalah bahwa dosen ini jelas berasumsi bahwa berfikir dan beriman itu dua hal yang berbeda. Artinya ketika seseorang itu berfikir, maka ia tidak sedang beriman atau tidak boleh beriman. Sebaliknya, ketika seseorang itu sedang beriman maka fikirannya harus istirahat. Ini seirama dengan pandangan Emanuel Kant (w.1804) bahwa teologi itu bukan ilmu atau senada dengan cara pandang dichotomis, agama tidak bisa jadi ilmu. Pastinya ini adalah cara pandang sekuler.
Tapi Islam tidak mengajarkan demikian. Sederhananya, Islam adalah agama yang dianut dan diimani dengan akal. Sebab seseorang yang dilahirkan sebagai Muslim sekalipun tidak wajib beriman dan berislam kecuali setelah dia dapat menggunakan akalnya alias mencapai umur Aqil dan baligh. Bahkan hadith Nabi menegaskan bahwa dasar keberagamaan dalam Islam itu adalah fikiran, tanpa fikiran berarti tidak ada keberagamaan religiusitas (al-dīn ‘aqlun la dīna liman la ‘aqla lah). Artinya beriman dalam Islam itu berdasarkan pada akal, dan ilmu ‘aqliyah itu bertujuan untuk beriman. Dalam hal ini Nabi menegaskan bahwa:
Barangsiapa tambah ilmunya, tapi tidak tambah petunjuknya, maka ia akan tambah jauh dari tuhannya (al-hadīth).
Hadith ini dapat diartikan begini: berangsiapa ilmunya tidak mengandung iman maka bertambahnya ilmu hanya akan menambah kesesatan. Logikanya, karena ‘ilm itu mengandung iman dan sebaliknya, maka sudah barang tentu bertambahnya ‘ilm itu akan menambah kekuatan iman.
Logika seperti ini akan lebih mudah difahami jika dibandingkan dengan kredo Katholik. Bagi mereka keimanan adalah asas dari pemahaman credo ut intellegam (saya beriman supaya saya faham). Tapi dalam Islam pemahaman yang menggunakan akal fikiran itu adalah asas keimanan. Maka dari itu ilmu dalam Islam adalah prasyarat iman, mencapi umur akil baligh adalah presyarat berislam. Non-Muslim yang baligh dapat masuk Islam setelah mamahami Islam, dan tidak boleh dipaksa. Maka kredo tersebut bagi Muslim harus dibalik menjadi intellego ut credam (saya faham supaya saya beriman).
Untuk mengetahui bagaimanakah proses berfikir dan beriman itu, perlu tahu pula kompleksnya perangkat jiwa manusia dalam Islam. Dalam Islam terdapat nafs (jiwa), sadr (dada), ‘aql (akal ), qalb (hati), Fu’ad (nurani), al-Lubb (akal fikiran yang beriman) dan lain sebagainya.
Menurut Hakim al-Tirmidhi (w. 320 H), qalb (hati) itu diibaratkan sebagai mata, sadr adalah putih mata, fu’ad adalah hitamnya pupil mata sedangkan lubb adalah cahaya mata. Itu semua disebut nafs sebagai potensi utamanya. Di dalam jiwa terdapat potensi qalb dan di dalam qalb terdapat sadr. Jika diibaratkan sebuah struktur kekuasaan qalb itu adalah raja dan jiwa itu adalah kerajaannya. “Jika rajanya baik – seperti sabda Nabi – maka baiklah bala tentaranya dan jika rusak maka rusaklah bala tentaranya”. Demikian pula baik-buruknya jasad itu tergantung pada hati (qalb). Hati (qalb) itu bagaikan lampu dan baiknya suatu lampu itu terlihat dari cahanya. Maka cahaya hati adalah ketaqwaan dan keyakinannya.
Sekarang marilah kita cermati dimanakah letak ilmu itu dalam diri manusia. Secara umum al-Ghazalī menyatakan bahwa:
“ilmu adalah kehadiran makna sejati dari benda-benda – dan segala kualitas, kuantitas, substansi dan esensi benda-benda itu – dalam jiwa yang tenang dan rasional, (al-nafs al-nÉtiqah mutma’innah)”….
Definisi al-Ghazalī (w.1111) ini mirip dengan definisi para ulama sezamannya. Dalam tradisi Islam ilmu diartikan sebagai sampainya makna kedalam fikiran (dhihn) dan sampainya fikiran kedalam makna. Ini mengindikasikan bahwa jiwa yang dimaksud al-Ghazalī adalah fikiran. Berarti ilmu itu berada di dalam jiwa, tapi jiwa sendiri memilki bagian-bagian yang tak terpisahkan dan saling berhubungan.
Berkaitan dengan letak ilmu al-Qur’an menjelaskan bahwa alat untuk memahami sesuatu adalah qalb (QS. al-A’raf 179). Namun, Hakim al-Tirmidhi menjelaskan bahwa tempat masuknya cahaya ilmu (termasuk ajaran Islam) adalah sadr. Ketika seseorang kita anggap sedang “berfikir” yang pertama-tama bekerja adalah sadr. Sadr adalah pintu masuk segala sesuatu ke dalam diri manusia termasuk nafsu amarah, nafsu birahi, cita-cita, keinginan. Akan tetapi sadr itu juga tempat masuknya ilmu yang datang melalui panca indera, termasuk khabar. Maka dari itu pengajaran, hafalan, dan pendengaran itu berhubungan dengan sadr. Dinamakan sadr karena merujuk kepada kata sadara (muncul), atau sadr (pusat).
Menurut Hakim al-Tirmidhi sadr menerima informasi awal dari segala sesuatu dan kemudian fuad memprosesnya. Di dalam fuad inilah tempat cahaya ma’rifah, ide, pemikiran, konsep dan pandangan. Kerja-kerja fuad itu kemudian dilimpahkan kepada qalb. Qalb adalah juga tempat bersemayamnya cahaya Iman, cahaya kekhusyu’an, ketaqwaan, kecintaan, keridhaan, keyakinan, ketakutan, harapan, kesabaran, kepuasan. Artinya qalb bisa berfungsi sebagai tempat iman dan juga sebagai tempat ilmu.
Informasi yang masuk kedalam qalb itu kemudian diproses di tempat yang paling tinggi yaitu lubb. Arti lubb yang sebenarnya adalah akal pikiran yang beriman. Ulul Albab adalah orang yang berakal fikiran tauhidi, maka lubb adalah tempat cahaya ketauhidan.
Disini jelas bahwa kita tidak bisa berfikir tanpa melibatkan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jika mindset dosen diatas ditrapkan maka bisa jadi fikiran kita bisa menjadi sangat rasional, tapi hati kita justru kufur kepada Allah. Kita juga bisa menjadi liberal, sekuler bahkan ateis, dan pada saat yang sama merasa sebagai ulul albab.
Jadi jika seseorang berfikir dan pada saat itu ia membuang jauh-jauh keimanannya, maka besar kemungkinan fu’ad, qalb dan lubb orang tersebut tidak digunakan, alias menganggur. Fikirannya tidak membawanya lebih dekat dengan Tuhannya. Segala amal perbuatannya menjadi bukan untuk ibadah. Buah fikirannya tidak memancarkan cahaya, karena cahaya ilahi tidak akan pernah masuk kedalam fikiran orang yang tidak niat untuk beribadah, tapi terjerumus kedalam kubangan maksiat.
Padahal dalam Islam segala aktifitas seorang Muslim, ilmiyah atau non ilmiyah adalah lillah untuk ibadah demi mencapai mardatillah sehigga akhir perjalanan pemikirannya dapat mencapai hikmah. Barangsiapa dikarunia Allah suatu hikmah, maka ia telah dikaruniai kebaikan yang berlimpah. Wallau a’lam bis showab.
Tulisan dimuat Jurnal Islamia Volume X No. 1 Januari 2016
Last modified: 28/04/2016