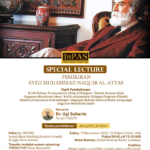Surabaya: Gedung GEMA IAIN Sunan Ampel terasa panas dan sesak. Beberapa buah kipas angin yang terpasang di sudut-sudut ruangan tak mampu mengatasi hawa panas yang berhembus dari luar. Nyaris semua kursi penuh terisi oleh mahasiswa IAIN, mahasiswa luar IAIN, serta masyarakat umum yang ingin menyaksikan Bedah Buku “Metodologi Studi Al-Qur’an – Menggugat Sakralisme Al-Qur’an Perspektif Islam Liberal”, Senin (21/12) dengan pembicara Ulil Abshar Abdallah (tokoh JIL), Dr. Imam Ghazali Said (Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Jawa Timur) dan Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag (Guru Besar Balaghah IAIN Sunan Ampel).
Bagi LIMI (Lembaga Ilmu Mahasiswa Independen) selaku panitia acara, momen ini merupakan momen yang membanggakan sekaligus menggembirakan, sebab mereka bisa bekerjasama dengan JIL (Jaringan Islam Liberal) yang bagi sebagian orang terasa “mencerahkan” dan “membebaskan”. Ditambah lagi event bedah buku ini mampu menyedot massa dalam jumlah besar, kendati ada upaya menggagalkan acara ini dalam bentuk selebaran berisi provokasi. “Semalam, sekitar jam 3, ada orang-orang yang menyebarkan selebaran bernada provokasi, berusaha menggagalkan terselenggaranya acara ini”, jelas Saidiman, koordinator JIL untuk IAIN Sunan Ampel. Selain berperan sebagai koordinator JIl untuk IAIN Sunan Ampel, Saidiman juga pegang peranan penting sebagai program officer di Jaringan Islam Liberal dan moderator mailing list Paramadina dan Formaci (Forum Mahasiswa Ciputat).
Moderator dengan penuh takzim menjelasan panjang lebar tentang latar belakang diselenggarakannya acara ini, antara lain untuk mentabayyunkan “gosip miring” yang selama ini kerap melanda Islam Liberal, meskipun tabayyun sudah pernah dilakukan oleh Forum Kyai Muda NU pada bulan Oktober lalu yang menghasilkan kesimpulan bahwa kemiringan Islam Liberal ternyata bukan gosip tapi fakta. Dalam forum yang difasilitasi oleh Gus Ali Masyhuri tersebut, Ulil terbukti membajak kitab karangan Imam Ar-Razi. Selain itu, acara ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa baru IAIN Sunan Ampel agar mereka memperoleh “kesegaran” dalam pemahaman Islam, termasuk mengenai desakralisasi Al-Qur’an. Ketidakjujuran intelektual semacam ini kemudian diulangi lagi oleh Ulil dalam bukunya dan penjelasan terhadap bukunya nya di IAIN Sunan Ampel. Kali ini Ulil memakai nama besar Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dan membajak kitab beliau, Al-Itqon fi Ulumil Qur’an untuk melegitimasi pemikiran liberalnya.
Ulil Abshar Abdallah yang dipuji setinggi langit oleh kalangan liberal tidak lebih dari corong orientalis yang melakukan duplikasi terhadap ide-ide dan konsep-konsep yang terdapat dalam tradisi keagamaan dan peradaban Barat. Parahnya lagi, Ulil Abshar sering melakukan pembajakan terhadap kitab para ulama klasik untuk mendukung pemikirannya yang landasan epistemologinya berasal dari tradisi keagamaan dan peradaban Barat.
Pemikiran yang dia tawarkan bukanlah pembaharuan, meskipun dia mengklaim begitu. Juga bukan ide yang kreatif dan inovatif hasil dari perenungan dan kajian terhadap struktur konsep dalam tradisi intelektual Islam. “Para orientalis sadar, bahwa mereka tidak bisa melawan Islam dengan kekuatan fisik. Akhirnya, mereka mengkader umat Islam untuk menghancurkan Islam dri dalam. Pepatah jawanya, ‘nabok nyilih tangan’,” jelas Prof.Dr.H.M. Roem Rowi, MA, salah seorang pakar ilmu bidang Tafsir dan Ulumul Al-Qur’an paling terkemuka di Indonesia. Prof. Roem Rowi yang juga guru besar ilmu Alquran dari IAIN Sunan Ampel Surabaya ini pernah menegur secara keras mahasiswanya di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel yang mulai meragukan Al-Qur’an sebagai kitab suci akibat terpengaruh pemikiran liberal.
Di awal-awal ulasannya, Ulil langsung mengkritik pendapat absolut yang menyatakan bahwa Al-Qur’an itu suci. ”Al-Qur’an dianggap suci karena ada sekelompok masyarakat yang menganggapnya demikian. Buku yang saya tulis bersama dua rekan saya ini merupakan upaya sederhana untuk mencoba melihat kembali Ulumul Qur’an dan tradisi melihat Al-Qur’an dengan lebih segar, lebih baru, dengan mencoba untuk melihat Al-Qur’an sebagai teks, mungkin dengan cara yang agak berbeda dengan cara yang selama ini dikenal dalam studi-studi Al-Qur’an yang klasik,” kata Ulil.
Nama Imam Al-Suyuthi dan karya pentingnya dalam Ulumul Qur’an, yakni kitab Al-Itqon fi Ulumil Qur’an, menjadi ’bemper’ yang Ulil pakai untuk meyakinkan peserta bedah buku dan pembaca bukunya, bahwa gagasan dasar metodologi studi Al-Qur’an ala Ulil dkk bukan berasal dari para orientalis dan para sarjana Islam yang menjadi muridnya, namun gagasan yang secara epistemologi lemah ini berasal dari pemikiran Imam Suyuth dalam kitab Al-Itqon. ”Jika Anda baca dengan baik, di dalam Al-Itqon fi Ulumil Qur’an itu kelihatan sekali bahwa Al-Qur’an itu adalah teks yang punya sejarahnya sendiri,” imbuhnya.
Tapi jurus tipu-tipu (baca : membajak kitab) yang dilancarkan Ulil ini segera ketahuan saat dilakukan cross check terhadap kitab-kitab yang dibajak oleh Ulil. Hal itu juga bisa diketahui dengan ’jurus justifikasi’ Ulil yang selalu mencoba mengaitkan antara pendapat ulama klasik yang lurus dengan pendapat intelektual Islam liberal yang menyimpang. Lihat saja ketika Ulil meloncat dari Al-Itqon ke karya kontroversial Nashr Hamid Abu Zayd, Mafhum Al-Nashsh : Dirasah fi Ulumil Qur’an. ”Dalam buku ini (Mafhum Al-Nashsh : Dirasah fi Ulumil Qur’an, red), Nashr Hamid pernah melontarkan statement yang membuat banyak orang marah. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur’an itu muntaj tsaqafi. Bahwa Al-Qur’an itu adalah produk dari lingkungan budaya. Nah, statement ini sebetulnya kalau dipahami secara proporsional tidak harus membuat kita marah. Kalau kita lihat Al-Itqon fi Ulumil Qur’an, di dalam Al-Itqon itu kelihatan sekali bahwa Al-Qur’an itu juga dipengaruhi oleh beberapa aspek dan beberapa hal di dalam lingkungan sejarahnya. Contoh yang paling bagus adalah Anda akan menjumpai di sana penjelasan yang panjang lebar tentang beberapa istilah ataupun kata, vocabulary, yang dipakai oleh Al-Qur’an yang berasal dari berbagai lingkungan bahasa, entah dari bahasa Aramaik, bahasa Syria, bahasa Ibrani, bahasa Etiopia, bahasa Yunani”, klaim Ulil.
Namun, ketika dilakukan cross check ke kitab Al-Itqon, Imam al-Suyuthi ternyata melakukan telaah kritis atas ditemukannya istilah-istilah asing dalam Al-Qur’an. Beliau menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keberadaan serapan bahasa non-Arab dalam Al-Qur’an. Mayoritas mereka seperti Imam Syafi’ (m. 204/820), Abu ’Ubaydah (m. 209/825), Ibn Jarir al-Tabari (310/923) dan Ibn Faris (m. 395/1004), menolak wujud kosakata asing di dalam Al-Qur’an karena Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab. Imam Syafi’i bahkan sangat membenci orang yang berpendapat demikian. Abu ’Ubaydah mengatakan : ”Sesungguhnya Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Siapa yang mengklaim bahwa selain bahasa Arab ada di dalamnya, maka ia telah melebih-lebihkan perkataan, dan barangsiapa yang mengklaim bahwa (kidzaban) [Q.S. An-Naba’ : 25,38] berasal dari bahasa Nabatean, maka ia telah membesar-besarkan pembicaraan”. Dalam pandangan At-Tabari, Ibn ’Abbas dan yang lain, kata-kata dalam Al-Qur’an tidak ditafsirkan dengan bahasa Persia, Ethiopia, Nabatean dll. Bahasa-bahasa tersebut saling berkaitan. Orang-orang Arab, Persia, Ethiopia berbicara dengan satu ucapan. Sedang penolakan Imam Syafi’i, Ibn Jarir al-Tabari, Abu ’Ubaydah dan Ibn Faris didasarkan pada firman Allah pada Surat Yusuf ayat 2, Surat Fushshilat ayat 2, Surat Al-Zumar ayat 28, Surat al-Shura ayat 7, Surat Al-Zhukhruf ayat 3, Surat Al-Shu’ara ayat 195, dan Surat Al-Ra’d ayat 37.
Masih menurut Imam Suyuthi dalam Al-Itqon, sekelompok ulama lain melihat kemungkinan terdapatnya bahasa non-Arab dalam Al-Qur’an. Pada kenyataannya memang terdapat kosakata non-Arab, tetapi yang sudah biasa digunakan oleh orang-orang Arab dan diperlakukan sebagaimana bahasa Arab yang fasih. Abu ’Ubaydah mengatakan, bahwa pendapat yang benar menurutnya adalah kosakata non-Arab itu pada mulanya memang bahasa Ajam (non-Arab, red) sebagaimana telah dikatakan oleh para fuqaha, hanya saja bahasa Ajam tersebut telah menjadi unsur bahasa Arab. Kosakata seperti itulah yang terdapat dalam Al-Qur’an. Orang yang mengatakan bahwa kosakata itu adalah bahasa Arab adalah benar, tetapi orang yang mengatakan bahwa kosakata itu adalah bahasa Ajam juga benar.
Yang tidak benar adalah ketika Ulil menyatakan bahwa karena adanya kosakata non-Arab dalam Al-Qur’an, maka bukan sesuatu hal yang tidak lazim kalau Al-Qur’an menyerap berbagai pengaruh linguistik di sekitarnya, sehingga siapapun boleh melakukan perubahan terhadap nash dan juga perubahan terhadap makna-makna aslinya untuk dapat didekonstruksi sesuai dengan realitas sosial. Dengan menyandarkan pendapatnya pada gagasan Nashr Hamid Ulil berkata bahwa di dalam memahami teks agama, kita perlu mempertimbangkan realitas, sebab seperti ditulis dengan cukup baik oleh Nashr Hamid Abu Zayd, bahwa sebuah teks yang namanya Al-Qur’an atau hadits, itu datang kepada manusia sebagai respon terhadap kenyataan sosial.
Di sini Ulil hanya menganggap Al-Qur’an itu melulu ’teks’ (rasm), sama seperti kajian teks Bible dalam tradisi Kristen, padahal asal Al-Qur’an adalah bacaan (qira’ah) yang diperdengarkan, barulah tulisan (rasm) mengikutinya. Dalam penjelasannya Ulil selalu menyebut ’teks Al-Qur’an’. Prinsip yang disepakati adalah al-rasm tabi’ li al-riwayah (tulisan teks mengikuti periwayatan). Oleh karena itu faktor periwayatan dari mulut ke mulut sangatlah penting. Hal ini telah dilakukan oleh para sarjana dan penghapal Qur’an yang memiliki otoritas ilmiah. Artinya, ilmu qiro’ah berasal dari Rasulullah SAW sendiri. Al-Qur’an diwahyukan secara lisan dan ungkapan lisan Rasulullah SAW kepada umat berupa teks sekaligus cara mengucapkan. Yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Para sahabat tidak ada yang menginovasi qiro’ah. Perbedaan qiro’ah memang diwarisi dan bersumber dari Nabi SAW.
Ulil yang tidak mau mengikuti metode ini, dengan mudahnya berkata bahwa validitas Al-Qur’an patut diragukan. ”Teks Al-Qur’an sebetulnya teks yang tidak seluruhnya bebas dari masalah. Ada masalah yang bisa didiskusikan panjang sekali, diantaranya soal kejanggalan gramatikal, soal perbedaan bacaan yang juga kadang-kadang membuat kita menjadi bertanya-tanya”, pungkasnya.
Berbeda dengan bedah buku, seminar atau diskusi pada umumnya, para pembicara pembanding yang dihadirkan mendendangkan ”lagu” yang sama dengan Ulil sebagai pembicara utama. Meski ahli balaghah, namun Prof. Dr. Husein Aziz tidak mengkritisi Ulil meski mungkin dia tahu Ulil melakukan kesalahan fatal.
Husein Aziz terjebak dalam kerancuan epistemologi. Bagi dia, ’mengetahui’ apa yang diingingkan Tuhan, adalah mustahil sebab pemikiran manusia itu relatif dan yang absolut hanya Tuhan. Pernyataan ini tidak bisa diterima secara epistemologis. Kebenaran dari Tuhan yang absolut itu telah diturunkan kepada manusia melalui Nabi dalam bentuk wahyu. Kebenaran wahyu yang absolut itu dipahami oleh Nabi dan disampaikan kepada manusia. Manusia yang memahami risalah Nabi itu dapat memahami yang absolut.
Seolah tidak mau kalah liberal dengan Ulil, Ghazali Said memberikan contoh dekonstruksi syari’ah yang belum disebutkan Ulil. Kali ini maslahah dipersoalkan. ”Karena tujuan diterapkannya hukum Islam adalah untuk menciptakan maslahah kepada umat manusia, maka maqasid syari’ah itu lebih utama daripada syari’ah. Setiap tindakan yang mengandung maslahah itu pasti mengandung syariah”, ungkapnya sambil tertawa. Bukan itu saja, dalil ushuliyyah yang berbunyi al-Ibratu bi umumillafzh, la bi khususi al-sabab (perintah itu karena adanya kata-kata umum dan bukan karena sebab khusus, red) dibalik menjadi al-Ibratu bi khususi al-sabab la umumillafzh (perintah itu karena adanya sebab khusus dan bukan karena kata-kata umum). Maksud dari sebab khusus di sini adalah konteks budaya. Jadi, perintah dan larangan dalam Al-Qur’an itu harus dipahami dalam konteks budaya ketika ia diturunkan. Padahal larangan meminum khamr, memakan daging babi, berjudi, dan berzina tidak berdasarkan konteks budaya. Pembagian warisan laki-laki dua kali lipat dari yang diterima perempuan juga demikian. Dengan merubah orientasi hukum secara kontekstual seperti yang dinyatakan Ghazali Said, maka banyak sekali hukum Islam yang didekonstruksi.
Pemilihan pembicara pembanding yang pro Ulil ini ternyata tidak lepas dari campur tangan Ulil. ”Ulil yang minta agar Ghazali Said jadi pembicara pembanding”, jelas Ahmad Fahrurrozi, ketua panitia bedah buku.
Sepanjang diskusi, tidak pernah sekalipun Ulil menyebut Hermeneutika, meski dalam buku ”Metodologi studi Al-Qur’an”, Hermeneutika digunakan Ulil dan kawan-kawan untuk penafsiran Al-Qur’an, bukan Tafsir. Hermeneutika merupakan sebuah metode penafsiran yang tidak boleh digunakan untuk menafsirkan Al-Qur’an karena berasal dari agama dan tradisi Barat, yang secara epistemologi sangat bertentangan dengan epistemologi Islam. Syarat utama dan pertama aplikasi hermeneutika adalah perubahan status teks Al-Qur’an dari teks Ilahi menjadi teks basyari (manusia). Ketika dikonfirmasikan kepada Ulil mengenai hal ini, dengan senyum merekah, Ulil menjawab, ”Habis tadi ga ada yang nanya sich…hermeneutika dan tafsir kan sama aja”. Dan hal ini turut diamini oleh Ghazali Said yang berdiri di samping Ulil. (Kar)
Last modified: 18/11/2023